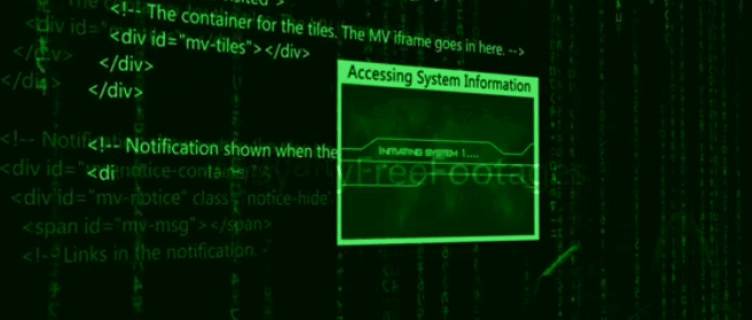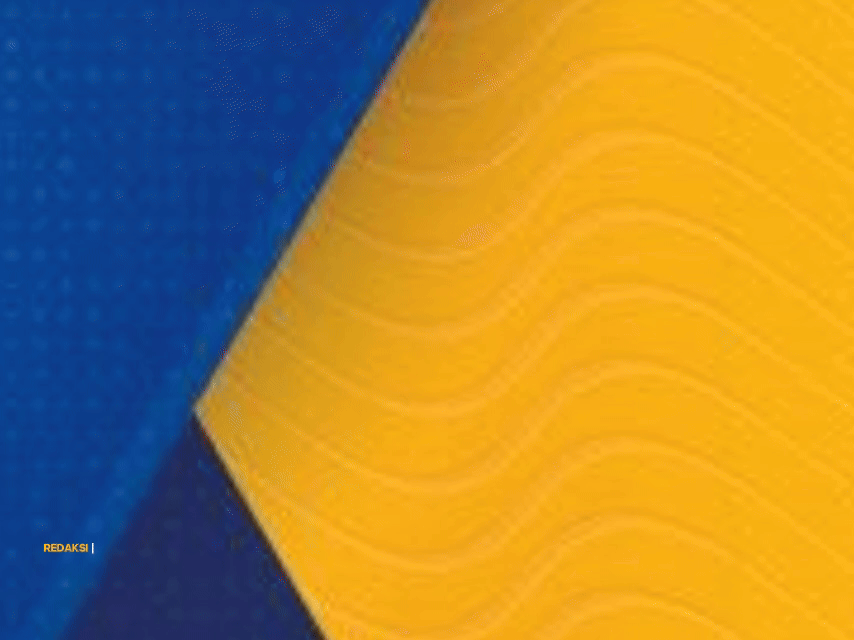Lebaran ajang silaturahmi keluarga. (Foto Yurnaldi/alinianews.com)
JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Lebaran tak lepas dari fenomena pulang kampung atau mudik tahunan para penduduk ke kampung halaman untuk merayakan Idulfitri dan bermaafan dengan seluruh anggota keluarga.
Tahun lalu, ada lebih dari 242 juta pemudik di seluruh Indonesia: angka tertinggi sepanjang sejarah. Kamu mungkin termasuk salah satu di antaranya.
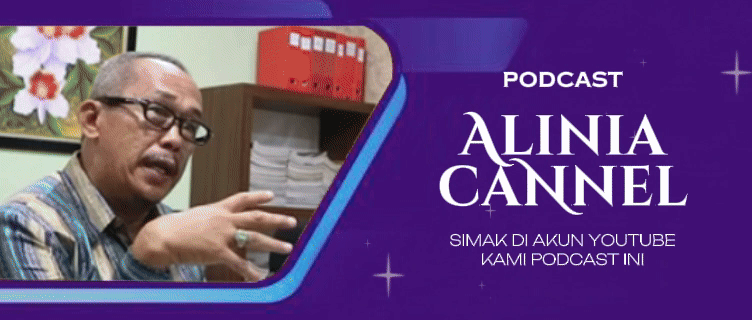
Para pemudik pun rela mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk mudik, rata-rata sekitar Rp3,88 juta per orang—setara lebih dari separuh upah minimum pekerja di Jakarta. Apalagi, saat musim lebaran harga tiket biasanya melambung. Tahun lalu, sekitar Rp71,8 triliun uang berputar dari aktivitas mudik saja.
Tingginya kebutuhan perjalanan pun membuat Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para penyedia layanan transportasi untuk menurunkan harga. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perekonomian tahun ini yang cenderung loyo.
Lantas, di tengah tren harga tiket mudik mahal dan kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja, mengapa orang tetap rela mudik saat lebaran?
Secara psikologis, jawabannya bermuara pada alasan kita untuk memenuhi ekspektasi sosial dan pulang ke “rumah psikologis”.
Ekspektasi sosial
Lebaran merupakan habitus atau kebiasaan kolektif masyarakat Indonesia yang telah lama berfungsi sebagai momen keluarga untuk berkumpul dan saling bermaafan.
 Suasana bertemunya keluarga besar saat lebaran. Usai Lebaran mereka berpisah karena ada yang kuliah di IPB Bogor, bekerja di Depok, kuliah di IPDN Jatinagor, dan ada yang tinggal di Padang. Idulfitri yang membuka serangkaian momen-momen kebersamaan muslim Indonesia saat lebaran. (Foto Yurnaldi/Alinianews.com)
Suasana bertemunya keluarga besar saat lebaran. Usai Lebaran mereka berpisah karena ada yang kuliah di IPB Bogor, bekerja di Depok, kuliah di IPDN Jatinagor, dan ada yang tinggal di Padang. Idulfitri yang membuka serangkaian momen-momen kebersamaan muslim Indonesia saat lebaran. (Foto Yurnaldi/Alinianews.com)
Sebagai kebiasaan kolektif, lebaran juga memuat norma dan adat-istiadat untuk menjelaskan apa yang baik, apa yang patut, dan apa yang dianggap bernilai. Norma dan adat istiadat ini diwariskan lintas generasi dan dilaksanakan secara bersama, berulang-ulang.
Norma ini juga membuktikan bahwa manusia tidak hidup dalam ruang hampa. Kita tumbuh bersama orang lain di sebuah lokasi dengan serangkaian adat istiadat yang telah berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat. Mayoritas norma bahkan telah hidup jauh sebelum kita lahir.
Momen lebaran pun menciptakan ekspektasi sosial bahwa seluruh anggota keluarga hadir secara fisik, bersatu dalam sebuah nuansa perayaan setelah menuntaskan ibadah puasa. Mereka pun terhubung untuk bermaafan dengan tetangga.
Selain ekspektasi untuk bermaafan, jenis makanan seperti ketupat, opor ayam, dan makanan lainnya merupakan ekspektasi lain yang membingkai ekspektasi umum tentang seperti inilah lebaran seharusnya.
Nah, mudik juga menjadi salah satu ekspektasi sosial tersebut. Saat lebaran, ada harapan para orang tua agar anak-anaknya yang merantau pulang kembali atau mudik.
Jadi, seseorang yang merantau akan rela untuk pulang meskipun harus menempuh perjalanan jauh dan membeli tiket yang mahal. Sebab, melalui mudik, kita berusaha merawat tradisi dan harapan keluarga.
Singkatnya, mudik merupakan sebuah pernyataan spasial (terkait lokasi) bahwa kita menghidupi nilai-nilai kultural sebagai anggota masyarakat di mana kita dibesarkan.
Kebutuhan membangun rumah psikologis
Alasan kedua mengapa masyarakat tetap pulang meskipun harga tiket sangat mahal adalah karena kita sedang memenuhi kebutuhan dalam membangun “rumah psikologis”.
Penelitian saya menunjukkan bahwa upaya membangun rumah psikologis tidak hanya merujuk kepada bangunan (house) atau ruang tertentu di rumah yang memberikan rasa nyaman. “Rumah” merupakan sebuah fenomena ketika kita terkoneksi kembali dengan semua komponen positif yang ada di sana.
Kebutuhan rumah psikologis ini terkait dengan identitas sebagai hal yang penting untuk manusia. Tengoklah kebiasaan kita mengenali orang lain dengan bertanya dan menjawab dengan menggunaan lokasi tertentu. “Kamu orang mana?”, “Saya adalah orang Nganjuk”.
Para ahli menyebutnya sebagai identitas spasial (place-based identity). Lokasi tertentu memberikan perasaan nyaman untuk kita, dan membuat kita menyebutnya sebagai rumah.
 Momen berkumpul dan makan bersama keluarga Busril -Ros di Kota Solok, dengan anak dan 24 cucu yang tinggal di sejumlah kota. (Foto Yurnaldi/Alinianews.com)
Momen berkumpul dan makan bersama keluarga Busril -Ros di Kota Solok, dengan anak dan 24 cucu yang tinggal di sejumlah kota. (Foto Yurnaldi/Alinianews.com)
Selain bangunan atau lokasi, rumah psikologis juga merujuk pada komponen lainnya seperti insan-insan yang kita sayangi seperti anggota keluarga. Komponen lainnya juga termasuk berbagai objek material yang penting untuk kita seperti benda-benda favorit, teknologi yang kita pakai, binatang peliharaan, aktivitas-aktivitas bersama, termasuk suasana yang ada di sana.
Seluruh komponen ini, ketika saling terkait dan memberikan rasa nyaman, menjadi material penyusun rumah psikologis bagi kita.
Dalam konteks lebaran, pulang merupakan ritual untuk terkoneksi dengan rumah psikologis karena menciptakan suasana khusus.
Ada momen spesial yang membuat komponen-komponen rumah psikologis saling berkelindan: makanan khas lebaran seperti opor dan kue nastar, kehangatan dan gelak tawa keluarga besar, suara latar bedug dan iklan sirup, perasaan sebagai satu keluarga, ingar bingar promosi di berbagai toko, dan masih banyak lagi.
Komponen-komponen ini merupakan sebuah himpunan (assemblage). Itulah mengapa, apabila komponennya tidak lengkap, misalnya ketika kue nastar atau opor tidak terhidang di meja suasananya menjadi tidak lagi sama.
Dua alasan mengenai inilah yang membuat kita merasa bahwa mudik merupakan sebuah aktivitas penting untuk kesejahteraan psikologis kita. Ini juga yang membuat harga tiket yang mahal dan perjalanan jauh tidak menghalangi keputusan seseorang untuk tetap mudik dan bertemu dengan keluarga saat lebaran tiba. Apakah kamu salah satu di antaranya?
(JONY EKO YULIANTO), Community and Applied Social Psychologist, Universitas Ciputra. Penulis pernah menerima beasiswa Massey University Doctoral Scholarship untuk menyelesaikan pendidikan doktoral di Massey University, Auckland, Selandia Baru/theconversation.com).