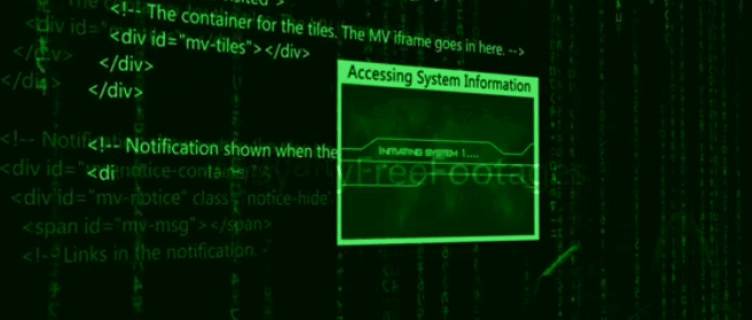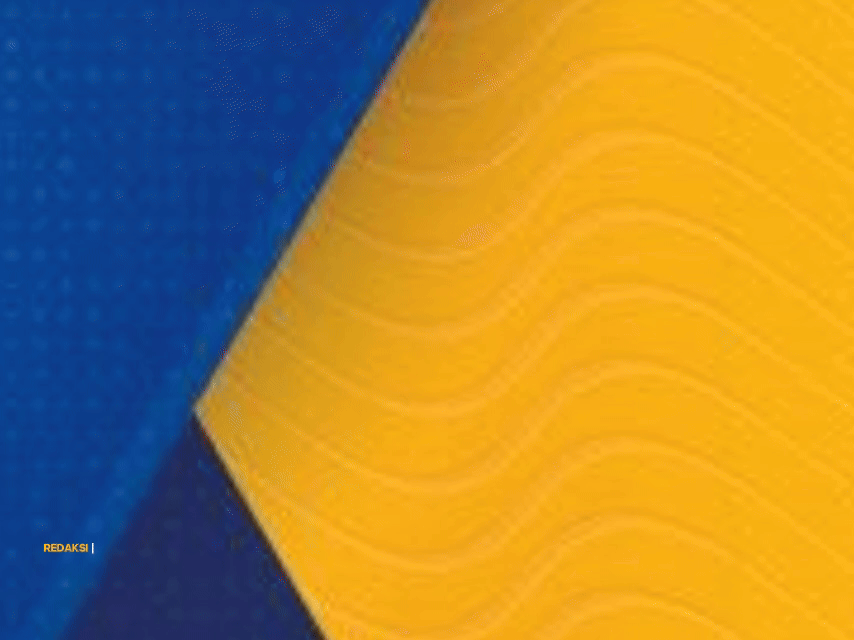Saat PTS Bertahan di Tengah Badai: Siapa yang Masih Peduli?
Oleh : Drs.H.Marlis,MN.C.Med ( Pemerhati Pendidikan )
Padang, 30 Desember 2025 ( Hasil Diskusi di Warkop Nipah )
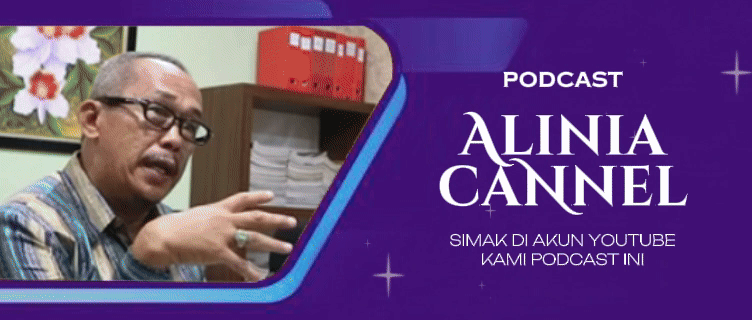
Di sebuah ruangan administrasi yang mulai sepi di sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Barat, deretan kursi mahasiswa tampak kosong. Dulu, setiap awal semester, ruangan itu penuh suara: mahasiswa yang menanyakan KRS, dosen yang bergurau, hingga petugas akademik yang sibuk melayani. Namun kini, hanya terdengar bunyi kipas angin tua yang berputar lambat.
Bagi banyak PTS di Indonesia, khususnya di daerah, suasana seperti ini mulai menjadi kenyataan pahit. Jumlah mahasiswa menurun drastis. Pendaftar baru berkurang dari tahun ke tahun. Sebagian program studi bahkan tidak mendapatkan mahasiswa sama sekali.
Di balik pintu rapat para pengelola kampus, ada kekhawatiran yang sama:
“Apakah kampus ini masih mampu membayar gaji bulan depan?”
“Sampai kapan kita bisa bertahan?”
Situasi PTS kini bukan sekadar sulit — tetapi berada pada titik kritis. PTS Berjuang, Sementara PTN Berlimpah Di sisi lain, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terus tumbuh dengan segala keistimewaannya. Dengan status PTN-BH, mereka leluasa membuka program baru, memperluas kuota mahasiswa, serta menawarkan ragam jalur penerimaan yang begitu menarik bagi lulusan SMA.
Hasilnya? PTN penuh sesak oleh puluhan ribu mahasiswa setiap tahun. PTS di seberang jalan justru harus memadamkan lampu lantai tiga karena tak sanggup menanggung biaya listrik akibat ruang-ruang kosong. Kontras itu semakin terasa menyakitkan ketika melihat kenyataan bahwa PTS-lah yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pendidikan tinggi Indonesia. Ketika Indonesia kekurangan kampus, PTS hadir. Ketika pemerintah belum mampu membangun infrastruktur pendidikan tinggi, PTS berdiri dengan segala keterbatasannya. Kini, setelah tiga dekade berjuang, banyak PTS justru seperti ditinggalkan di medan pertempuran.
Aspirasi dan Keluhan Mantan Rektor PTS Kota Padang
Seorang mantan Rektor PTS di Kota Padang, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, memberikan pernyataan yang begitu jujur sekaligus menyentuh:
> “Saya memimpin PTS selama hampir lima tahun. Kami tidak pernah menyerah untuk menjalankan pendidikan dengan segala keterbatasan. Namun kenyataan sekarang terlalu pahit. Penurunan mahasiswa bukan sekadar tantangan — ini ancaman eksistensi. Banyak kampus kecil di daerah seperti sedang menunggu waktu untuk tutup.”
Beliau melanjutkan dengan suara berat:
> “Kami merasa pemerintah seperti lupa bahwa PTS pernah menjadi penyelamat pendidikan Indonesia. Ketika perguruan tinggi negeri tidak mampu menampung lonjakan lulusan SMA, PTS-lah yang membuka pintu luas-luas. Tapi di saat kami berada di titik terendah, siapa yang datang membantu?”
Keluhan terbesarnya adalah soal ketimpangan kebijakan:
> “PTN diberi ruang dan fasilitas luar biasa. PTS hanya diberikan regulasi yang ketat, beban akreditasi berat, dan pengawasan yang kadang tidak mempertimbangkan realitas lapangan. Kami harus bertarung dalam pertandingan yang sejak awal tidak seimbang.”
Sebelum mengakhiri pembicaraan, ia menyampaikan satu aspirasi yang menggambarkan jeritan banyak PTS:
> “Kami tidak meminta disamakan dengan PTN. Kami hanya ingin ada kebijakan afirmatif yang realistis dan humanis — agar PTS tidak mati pelan-pelan. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat.”
Biaya Operasional Membengkak, Mahasiswa Menyusut
Di balik papan nama PTS yang terlihat kokoh, ada realitas yang jarang disadari: Listrik dan internet kampus tetap harus dibayar. Gaji dosen dan staf harus tetap dipenuhi. Gedung harus dirawat. Akreditasi butuh biaya besar. Sistem informasi akademik tidak bisa berhenti. Pemasukan PTS hanya dari dua sumber: mahasiswa dan mahasiswa. Ketika mahasiswa menurun, runtuhlah seluruh struktur.
Satu per Satu Berguguran
Beberapa tahun terakhir, fenomena ini makin terlihat jelas: PTS tutup, PTS bergabung, PTS merumahkan dosen, dan bahkan PTS tidak sanggup menerima mahasiswa baru. Jumlahnya tidak sedikit, dan gelombangnya semakin besar. Sayangnya, tidak banyak yang menyadari. Lebih sedikit lagi yang peduli.
Pertanyaan Besar: Apakah Pemerintah Tidak Lagi Peduli?
Pertanyaan ini kian mengemuka:
“Apakah pemerintah sudah tidak peduli dengan PTS?”
“Apakah PTS dibiarkan berguguran begitu saja?” Padahal: 60% mahasiswa Indonesia pernah atau masih kuliah di PTS. PTS meningkatkan akses pendidikan di luar kota besar. PTS menjadi pendorong mobilitas sosial jutaan keluarga. PTS membantu pemerataan peluang di tingkat daerah.Jika PTS tumbang, yang hilang bukan sekadar kampus — tetapi pintu masa depan anak-anak bangsa.
Siapa yang Akan Berdiri untuk PTS?
Diperlukan:
Kebijakan afirmatif yang nyata dan berkesinambungan
Insentif pendanaan bagi PTS yang rentan
Regulasi yang proporsional, bukan membebani
Kemitraan yang sehat dan saling menguatkan
Tindakan cepat sebelum korban berikutnya jatuh
PTS tidak meminta keistimewaan. PTS hanya meminta kesempatan untuk tetap hidup.
Penutup: Sebuah Jeritan Senyap
Di meja kerjanya yang penuh dokumen program studi dan tagihan bulanan, sang mantan rektor menyampaikan satu kalimat terakhir:
> “Kalau PTS mati, kita bukan sedang menyelamatkan PTN. Kita sedang kehilangan salah satu pilar penting pendidikan bangsa.”
Kini, sudah saatnya semua pihak membuka mata.
Karena jika PTS terus dibiarkan berguguran, maka dampaknya akan terasa bukan hanya hari ini, tapi puluhan tahun ke depan. (*/ Marlis Alinia – Mantan ASN )