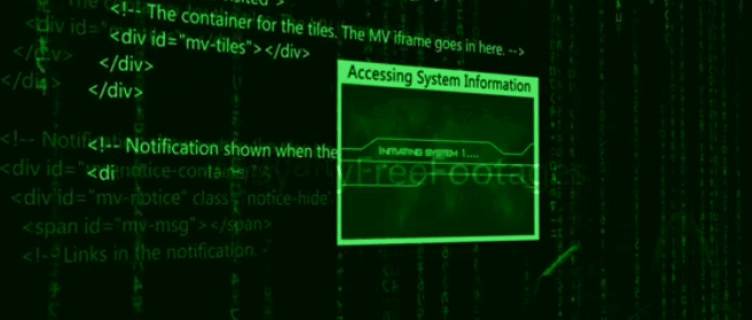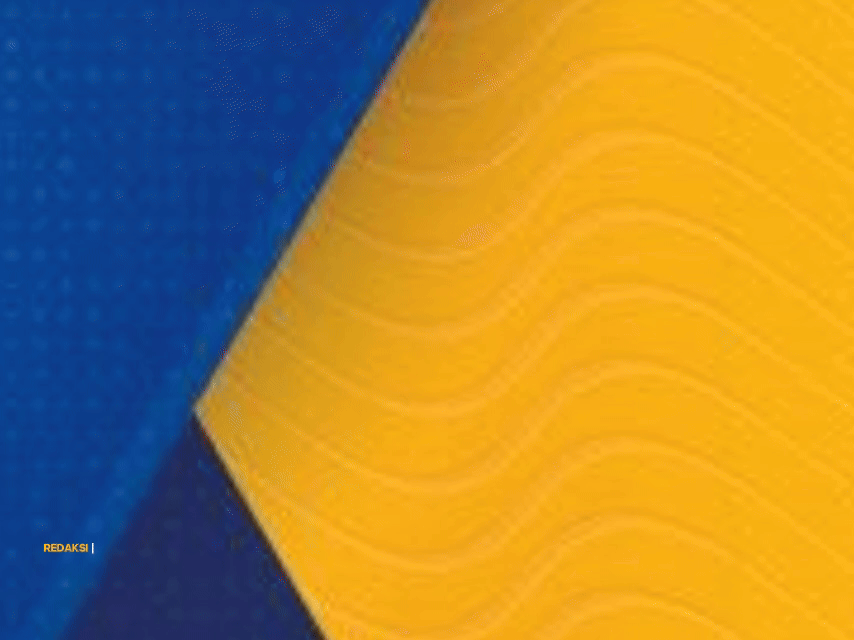Oleh MAYA LESTARI GF, Novelis, Penulis Buku, Esais, dan Mentor Menulis.
YOGYAKARTA, ALINIANEWS.COM — Barusan saya membaca sebuah postingan Instagram. Isinya tentang sebuah kisah inspiratif. Saya dulu cukup suka membaca kisah-kisah seperti ini di medsos. Saya suka membaca kisah resiliensi orang-orang. Dari mereka, saya belajar bahwa ketahanan manusia itu nyaris gak ada batasnya.
Namun, dengan cepat saya meninggalkan postingan itu. Hal yang sama juga terjadi saat saya membaca postingan-postingan serupa. Bahkan postingan berbau konspirasi yang kadang menarik minat saya, karena bisa memberi inspirasi penulisan cerita, sekarang mulai jarang saya baca. Sebabnya sederhana: polanya mirip semua, gayanya sangat khas AI. Informasi sangat sedikit, yang banyak adalah repetisi kosong gak ada artinya.
Belakangan, narasi-narasi semacam ini mulai membanjiri media sosial. Beberapa waktu lalu, saya membaca sebuah review singkat seseorang akan sebuah buku di Threads. Sekali lihat saya langsung tahu dia cuma copy paste konten AI. Dia bilang, dia baru saja baca buku tersebut dan sangat terkesan. Tapi judul yang ia tulis salah, sinopsisnya salah, poin-poin yang dia sampaikan tentang buku itu salah semua. Tulisan dan datanya yang ngawur itu khas AI. Bagaimana bisa seseorang membuat konten membaca buku tapi nggak membaca bukunya? Kemungkinan besar dia menyuruh AI mencari sebuah buku untuk diulas, lalu hasilnya dicopas.
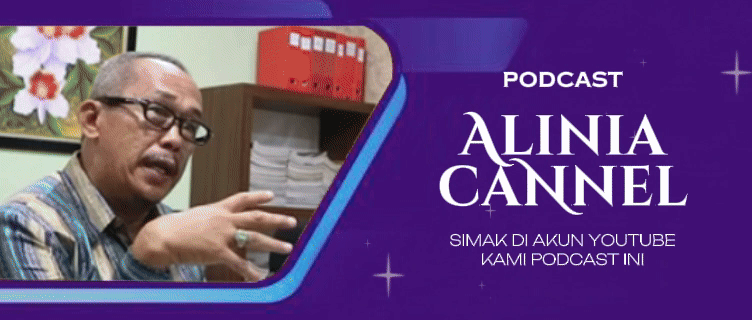
Beberapa waktu lalu saya diminta menyeleksi naskah. Dari semua naskah yang masuk, saya harus memilih 30 untuk dibukukan. Sebagian naskahnya ditulis pakai AI. Saya mengenalinya dari pola penulisan AI yang khas. Sejak diluncurkan sekitar 2022, saya mulai mempelajari AI Generatif untuk mengenalnya lebih jauh, jadi saya cukup akrab dengan pola-pola karya yang dihasilkannya. Dugaan saya akan karya AI ini diperkuat pada sesi wawancara. Para penulisnya bahkan nggak bisa menjabarkan apa yang sudah mereka ‘tulis’.
Apa yang membuat saya kurang sreg dengan fenomena ini adalah: kebiasaan copas AI mulai menyasar anak-anak. Mereka menyelesaikan tugas-tugas belajarnya dengan AI. Beberapa di antaranya dengan cerdik mengubah beberapa bagian. Namun, itu tentu saja membuat tulisannya jadi cukup aneh, karena beberapa paragraf tertulis dengan gaya X, paragraf lain dengan gaya Y. Ketidaksinkronan ini dengan mudah saya notice.

Apakah anak-anak dan remaja yang memakai AI itu salah? Nope, saya kira yang salah adalah sistem pendidikan yang melingkupi mereka, yang membuat mereka tidak bisa membedakan mana hasil berpikir sendiri, mana yang bukan. Tidak mampu membuat mereka menikmati kesenangan mempelajari sesuatu, berimajinasi, dan mengolah apa yang ada di pikiran menjadi sesuatu yang konkret. Karena orientasinya hasil, bukan pengembangan diri, anak-anak ini tidak sadar kalau mereka sebenarnya sedang menipu diri sendiri.
AI Generatif bisa menjadi teman belajar jika penggunanya punya kemampuan berpikir kritis, punya rasa ingin tahu, punya kemampuan imajinasi yang tinggi. Prompt yang akan mereka masukkan pun akan bersifat evaluatif-reflektif (lemampuan literasi level 3) bukan sekadar apa (kemampuan literasi level 1). Pada masa kanak-kanak hingga setidaknya masa remaja awal (15 th) saya pikir yang perlu dikuatkan dalam diri anak-anak adalah budaya senang mengembangkan diri ini. Otak berkembang dengan tantangan. Semakin banyak pengalaman belajar nyata (inquiry, hands on learning, dll), semakin banyak sinapsis syarafnya terbentuk. Itulah sebabnya kenapa rata-rata petinggi teknologi dunia menganut prinsip ‘late is better’ bagi anak-anaknya belajar dengan gawai/aplikasi. Sebab, perkembangan otak yang terampas mesin di waktu kecil, akan sulit ditarik lagi saat dewasa.
Direktur AI Artium, Cauri, misalnya, memilih mengajarkan anaknya bagaimana sistem kerja alam ini (fisika) terlebih dahulu. Bahkan Cauri pun mengakui, AI baru akan benar-benar maksimal mendukung kerja manusia, jika penggunanya memiliki kemampuan berpikir kritis. Karena itu, sebenarnya memberi keleluasaan kepada anak/remaja menggunakan AI Generatif, sama dengan memberi racun ke otak mereka. Guru-guru sebuah SMA yang saya beri pelatihan penguatan literasi akhir tahun lalu mengakui: “Kalau kami melarang anak-anak pakai Chat GPT, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan, bahkan yang sangat sederhana.” Yah, artinya apa? Artinya bahkan anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran apapun, sebab, semua diserahkan ke Chat GPT.

Dalam waktu tak berapa lama lagi, dunia kita akan dipenuhi oleh narasi-narasi AI yang tak punya pengalaman. Kita akan dihujani narasi berpola sama, cenderung netral dan datar, penuh bunga-bunga kata, namun nyaris gak ada isinya. Pada mulanya mungkin itu terlihat wow …tapi, hasrat manusia akan makna tak bisa dibohongi. Dengan segera, setelah kita dibanjiri narasi-narasi AI, kita akan jenuh, lalu kita akan mencari narasi-narasi sungguhan yang lahir dari kekayaan pengalaman, perenungan, dan pikiran kritis.
Ada satu pertanyaan: kapan orang-orang tanpa kemampuan imajinasi, kreativitas, dan pikiran kritis akan tersisih? Ya saat semua objek, baik orang maupun mesin, bisa memproduksi narasi/karya yang sama, maka saat itulah yang dibutuhkan sesuatu yang kreatif, imajinatif, dan reflektif. Sesuatu yang hanya hadir, jika kemampuan itu dipupuk dan dirawat dari kecil.