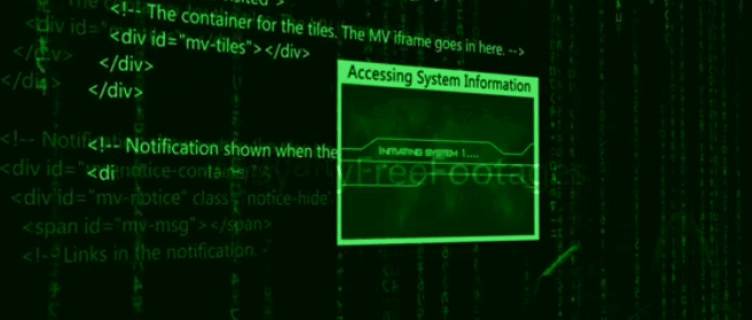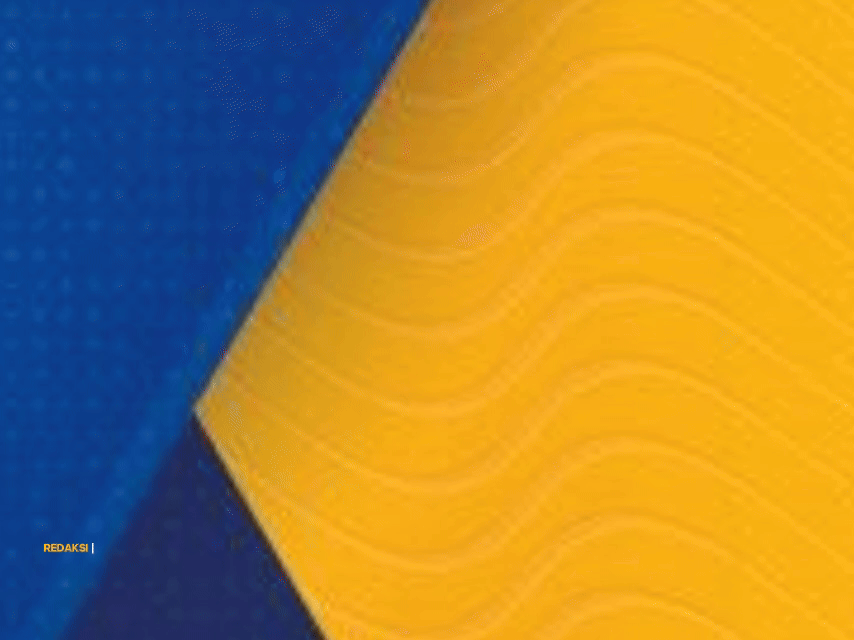Oleh:
Musfi Yendra., S.IP., M.Si.
Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat
KETERBUKAAN informasi publik merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), negara menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik.
Lembaga yang menjadi garda utama pelaksana mandat ini adalah Komisi Informasi (KI)— lembaga independen yang memiliki dua agenda besar sekaligus, yaitu penyelesaian sengketa informasi publik dan monitoring serta evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
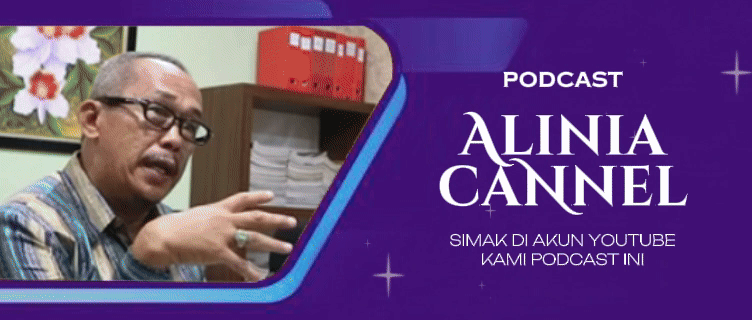
Dua agenda tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Perki Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik.
Namun, dalam pelaksanaannya, kedua agenda itu sering kali berjalan sendiri-sendiri, tanpa hubungan yang kuat, sehingga menimbulkan persoalan konsistensi dan akuntabilitas lembaga di mata publik.
Perki Nomor 1 Tahun 2013 memberikan pedoman bagi penyelesaian sengketa informasi publik. Sengketa terjadi ketika pemohon merasa haknya atas informasi diabaikan, ditolak, atau tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah. Dalam konteks ini, Komisi Informasi berperan sebagai lembaga quasi peradilan yang memeriksa, memutus, dan menetapkan sengketa antara badan publik dan masyarakat.
Proses ini merupakan bentuk pertanggungjawaban badan publik kepada rakyat dan menjadi cermin kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan. Ketika suatu lembaga publik dinyatakan kalah dalam putusan sengketa, artinya lembaga tersebut secara hukum terbukti melanggar kewajiban untuk membuka informasi.
Sayangnya, dalam praktiknya, banyak lembaga publik yang berulang kali menjadi pihak tergugat dalam sengketa serupa, menunjukkan bahwa keterbukaan belum menjadi budaya birokrasi, melainkan hanya kewajiban administratif yang dijalankan karena tekanan hukum.
Sementara itu, Perki Nomor 1 Tahun 2022 menugaskan Komisi Informasi untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap kepatuhan badan publik dalam menjalankan kewajiban keterbukaan. Melalui kegiatan ini, Komisi Informasi menilai sejauh mana badan publik telah menyediakan informasi berkala, menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta membangun sistem pelayanan informasi yang transparan.
Hasil monev kemudian dipublikasikan dalam bentuk penilaian dengan kategori yaitu “Informatif”, “Menuju Informatif “Cukup Informatif”, “Kurang Informatif” hingga “Tidak Informatif”. Secara ideal, Monev ini menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dan memperkuat akuntabilitas lembaga negara.
Namun, di sinilah muncul dilema serius. Dalam beberapa kasus, badan publik yang sedang atau baru saja kalah dalam sengketa informasi publik justru mendapat nilai tinggi dalam penilaian Monev dan dianugerahi predikat “Informatif”. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar dari publik: bagaimana mungkin lembaga yang telah dinyatakan melanggar keterbukaan informasi justru dianggap sebagai contoh terbaik keterbukaan?
Situasi semacam ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Komisi Informasi sendiri. Dalam pandangan publik, lembaga pengawas yang seharusnya konsisten menegakkan prinsip keterbukaan justru tampak inkonsisten ketika memberikan penghargaan kepada pihak yang baru saja dikoreksi melalui putusan hukum.
Diakui dilema ini memperlihatkan adanya kelemahan sistemik dalam regulasi dan koordinasi internal Komisi Informasi. Tidak ada mekanisme dalam Perki Nomor 1 Tahun 2022 yang secara tegas menghubungkan hasil penyelesaian sengketa dengan proses dan hasil Monev.
Akibatnya, kedua sistem pengawasan berjalan di jalur paralel tanpa saling terhubung. Jalur sengketa menilai kepatuhan hukum, sedangkan jalur monev menilai kepatuhan administratif. Ketika keduanya tidak disinergikan, muncul celah di mana lembaga publik bisa saja mengabaikan putusan sengketa tanpa khawatir reputasinya tercoreng karena penilaian monev tidak mempertimbangkan rekam jejak pelanggaran tersebut.
Kelemahan ini tentu berdampak pada akuntabilitas Komisi Informasi di hadapan publik. Di satu sisi, Komisi Informasi bertindak sebagai pengadil yang menegur badan publik karena tidak transparan. Di sisi lain, lembaga yang sama memberikan penghargaan keterbukaan kepada pihak yang sama, hanya karena memenuhi aspek administratif dalam monev.
Jika dibiarkan, wajar kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa Monev hanya agenda seremoni tahunan, bukan instrumen evaluasi yang benar-benar mencerminkan tingkat keterbukaan yang substantif. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Indikator penilaian Monev ini juga sangat ketat. Hasil Monev sendiri bisa diakses secara terbuka oleh publik ke Komisi Informasi.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah reformasi kelembagaan dan harmonisasi regulasi. Komisi Informasi Pusat yang memiliki kewenangan membuat regulasi perlu membangun integrasi antara hasil penyelesaian sengketa dan penilaian Monev. Hasil putusan sengketa seharusnya menjadi salah satu indikator penilaian dalam Monev berikutnya.
Badan publik yang kalah dalam sengketa perlu ditempatkan dalam kategori khusus — misalnya “perlu pembinaan” atau “perlu perbaikan keterbukaan” — agar publik mengetahui rekam jejak kepatuhan mereka secara transparan.
Selain itu, Komisi Informasi juga harus memperkuat akuntabilitas internal dengan membuka data hasil Monev dan tindak lanjut putusan sengketa kepada publik. Berapa banyak putusan yang dijalankan, berapa yang diabaikan, dan bagaimana hasil monev berkontribusi pada perubahan sistem harus disampaikan secara terbuka.
Keterbukaan informasi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga tentang konsistensi moral dan kelembagaan dalam menegakkan transparansi. Komisi Informasi tidak cukup menjadi lembaga yang memutus sengketa, tetapi juga harus menjadi penjamin berjalannya sistem keterbukaan secara berkelanjutan.
Dua agenda besarnya: penyelesaian sengketa dan Monev — seharusnya berjalan beriringan dalam satu semangat yang sama: menjaga integritas keterbukaan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Tanpa konsistensi dan integrasi kebijakan, Komisi Informasi terancam berisiko terjebak dalam paradoks — menjadi hakim yang memutus pelanggaran di satu sisi, tetapi memberi penghargaan di sisi lain kepada pihak yang sama.
Tentu dilema ini harus segera disikapi, karena menyangkut kredibilitas Komisi Informasi sendiri, dan juga badan publik pelaksana keterbukaan informasi publik. Ini akan menjadi masukan dari Komisi Informasi Sumatera Barat untuk diteruskan ke Komisi Informasi Pusat.