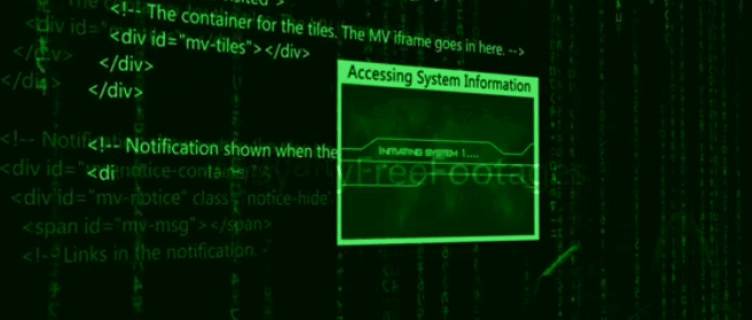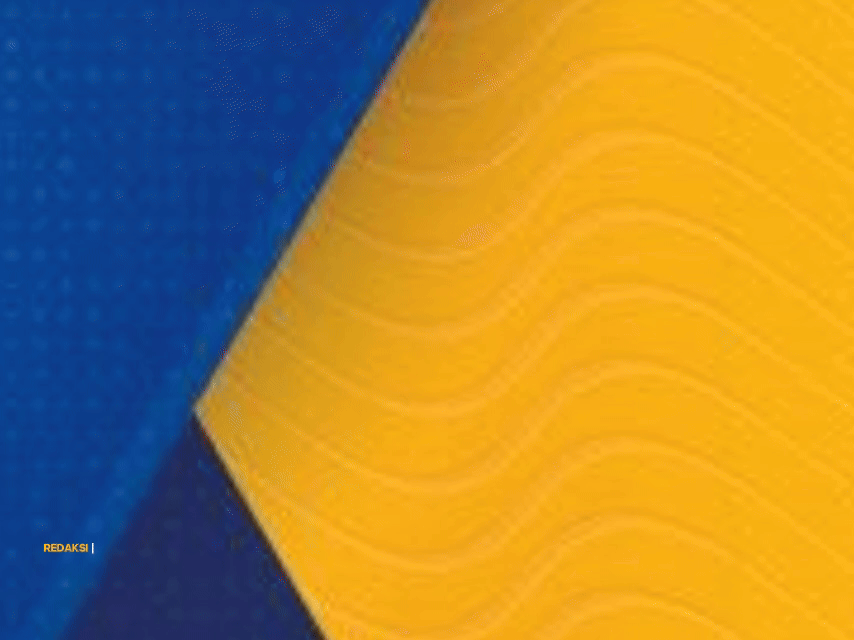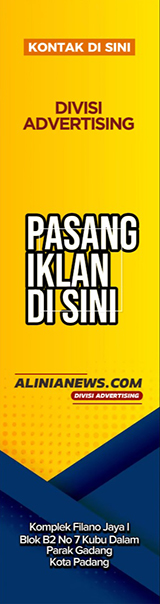ALINIANEWS.COM — Fenomena flexing pejabat dan keluarganya kembali marak di ruang publik, terutama di media sosial. Pamer kemewahan dari mereka yang seharusnya memberi teladan justru menimbulkan kegaduhan sosial. Publik mempertanyakan: untuk siapa sesungguhnya para pejabat itu bekerja?
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu mengimbau agar pejabat hidup sederhana. Namun, imbauan itu terasa hampa. Tanpa regulasi dan pedoman yang jelas, pesan moral tersebut tak ubahnya angin lalu. Inilah yang disoroti Guru Besar IPDN sekaligus mantan Dirjen Otonomi Daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan. Menurutnya, imbauan lemah tanpa dasar regulasi tidak akan mengubah perilaku pejabat. “Kalau hanya bicara sederhana, tanpa pedoman perilaku, orang bisa memaknainya bebas-bebas saja,” ujarnya.
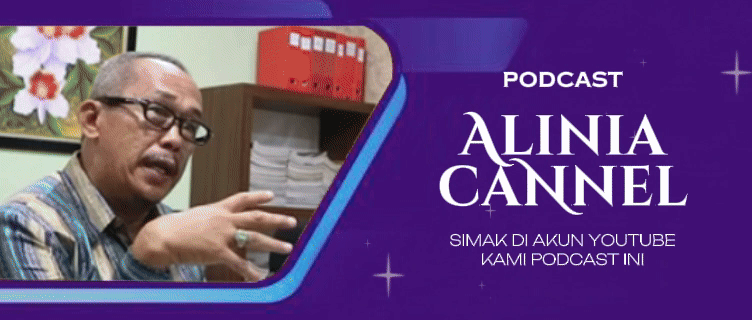
Kelemahan terbesar kita adalah ketiadaan pedoman perilaku penyelenggara negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebenarnya sudah dibekali kode etik sejak masa prajabatan, karena mereka adalah abdi negara. Namun pejabat politik non-ASN—politisi, artis, pengusaha—tidak pernah melalui proses internalisasi etika. Mereka bisa langsung duduk di kursi parlemen atau jabatan publik tanpa bekal etika pemerintahan yang memadai. Tak heran jika perilaku glamour dan gaya hidup mewah lebih sering muncul dari kalangan ini.
Padahal, di banyak negara, ada yang disebut government ethics: pedoman perilaku resmi, mengikat, dan diawasi secara ketat. Indonesia pun pernah mengenal program hidup sederhana di era Presiden Soeharto. Meski dijalankan terbatas dan penuh paradoks, setidaknya ia pernah menjadi agenda kabinet. Ironisnya, setelah era reformasi, agenda itu lenyap dari Asta Cita maupun Nawa Cita. Yang muncul justru kebalikannya: gaya hidup berlebihan pejabat dan keluarganya yang semakin dipertontonkan di ruang publik.
Sudah saatnya pemerintah berhenti menebar imbauan. Yang dibutuhkan adalah regulasi yang jelas dan mengikat, bahkan hingga level undang-undang. Kita perlu memiliki UU Etika Pemerintahan, yang berlaku bagi semua: Presiden, menteri, kepala daerah, anggota DPR/DPD/DPRD, hingga ASN. Pedoman itu harus mencakup semua aspek, mulai dari gaya hidup pribadi, pesta keluarga, hingga perjalanan dinas ke luar negeri. Dengan begitu, pejabat publik memiliki rambu yang jelas dalam menampilkan dirinya di hadapan rakyat.
Tentu regulasi tanpa pengawasan hanya akan berhenti di atas kertas. Karena itu, mekanisme kontrol harus berlapis. Pertama, pengawasan internal oleh pimpinan lembaga dan aparat pengawas internal pemerintah. Kedua, pengawasan eksternal oleh publik sebagai watchdog. Bila ada pedoman resmi, masyarakat dapat menilai apakah pejabat mematuhinya atau tidak. Transparansi di era digital justru bisa menjadi alat kontrol paling efektif.
Intinya, imbauan sederhana tidak akan pernah cukup. Yang diperlukan adalah teladan nyata, aturan main yang tegas, dan keberanian politik untuk mengikat diri. Pertanyaan yang layak diajukan kepada pemerintah hari ini adalah: beranikah membuat aturan yang juga mengikat Presiden, menteri, dan seluruh pejabat publik?
Jika jawabannya tidak, maka kita harus bersiap menyaksikan fenomena flexing pejabat terus berulang. Akibatnya, kepercayaan publik kian runtuh, jarak pemerintah dengan rakyat semakin lebar, dan pejabat kehilangan martabat sebagai teladan. Jika jawabannya ya, inilah saatnya menorehkan sejarah baru: membangun etika penyelenggara negara sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bermartabat. (YURNALDI)