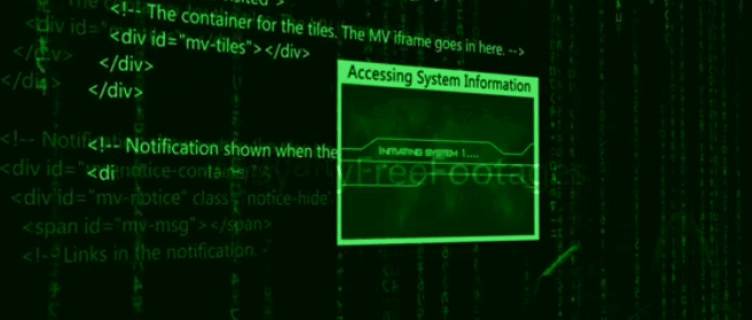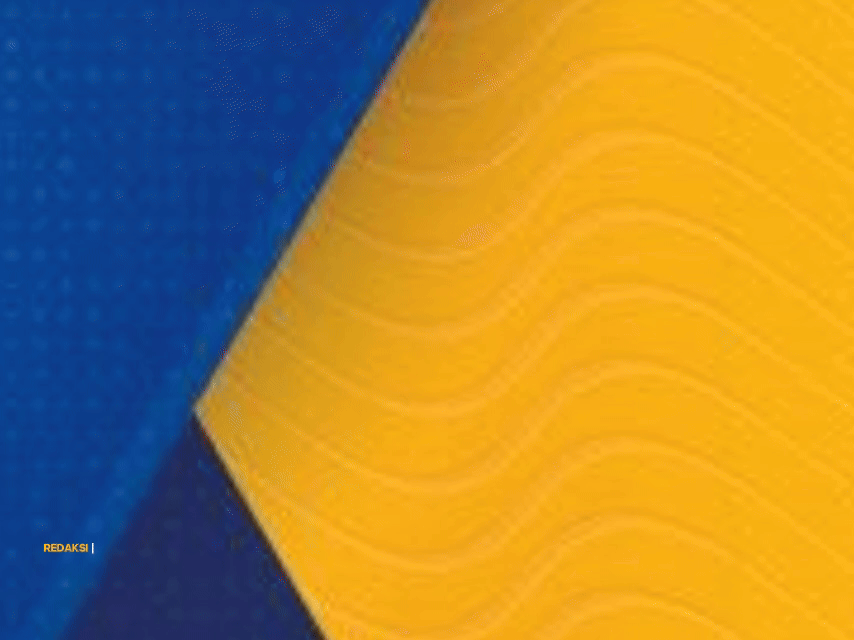ALINIANEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah besar yang menjadi pusat sorotan publik: memberikan abolisi kepada Tom Lembong, dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, dua tokoh politik yang sebelumnya divonis dalam kasus hukum. Kedua keputusan itu kemudian dipuji sebagian kalangan sebagai simbol “kearifan negara” dan langkah rekonsiliasi politik. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang memandangnya sebagai bentuk kompromi kekuasaan yang melemahkan supremasi hukum.
Abolisi terhadap Tom Lembong dilakukan bahkan saat vonis belum berkekuatan hukum tetap. Artinya, negara memutus proses peradilan sebelum tuntas. Ini memunculkan pertanyaan: apakah putusan pengadilan dianggap keliru? Jika ya, mengapa tidak dibiarkan banding berjalan sebagaimana mestinya? Jika tidak, mengapa dihentikan?
Sementara itu, amnesti kepada Hasto Kristiyanto, tokoh penting PDIP, datang dalam momentum menjelang kemerdekaan. Tak lama setelah itu, muncul seruan Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader PDIP mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebuah peristiwa yang oleh publik mudah dimaknai sebagai barter politik ketimbang niat tulus membangun rekonsiliasi.
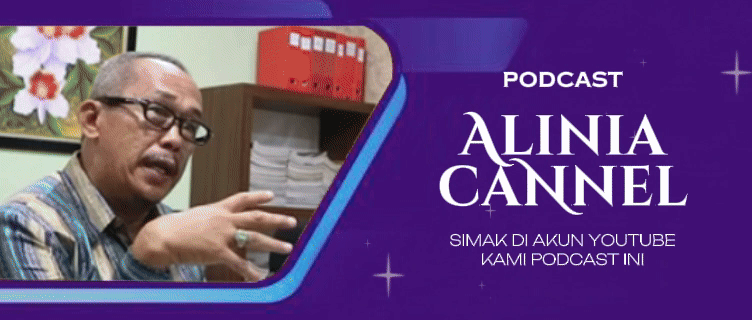
Editorial ini tidak hendak menolak upaya perdamaian atau pengampunan. Dalam sejarah bangsa, kita telah belajar dari pengalaman Aceh, Papua, bahkan Afrika Selatan bahwa rekonsiliasi bisa jadi jalan yang mulia. Tetapi rekonsiliasi yang otentik tidak cukup dilakukan hanya di ruang elite dan tanpa pengakuan kesalahan. Ia mesti menyentuh keadilan publik.
Kita tidak ingin bangsa ini tumbuh dalam dendam. Namun kita juga tidak bisa membiarkan keadilan tumbuh dalam kompromi. Ketika negara menggunakan kewenangannya untuk menghapus proses hukum atau hukuman, maka negara juga berkewajiban memberikan alasan moral dan hukum yang terang-benderang kepada rakyat.
Jika tidak, publik akan merasa bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada segala bentuk perpecahan politik.
Langkah pengampunan sebaiknya dibarengi dengan: Transparansi proses dan alasan hukum yang kuat; Pengakuan kesalahan oleh pihak terlibat; Reformasi institusional agar kasus serupa tidak terulang; Ruang dialog publik, bukan sekadar komunikasi satu arah dari negara.
Karena sejatinya, kearifan sebuah negara tidak diuji saat ia memberi ampunan, tetapi saat ia memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan—bukan disubstitusi oleh kompromi kekuasaan.(YURNALDI)