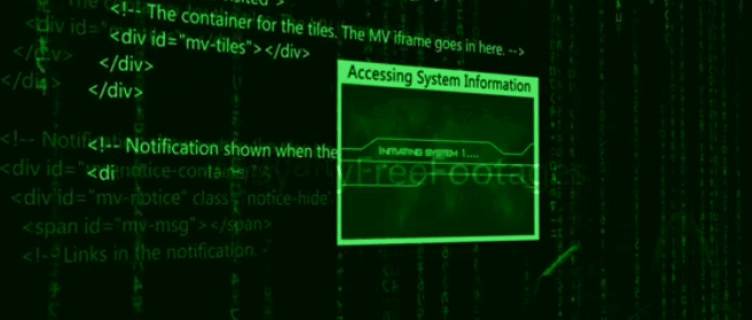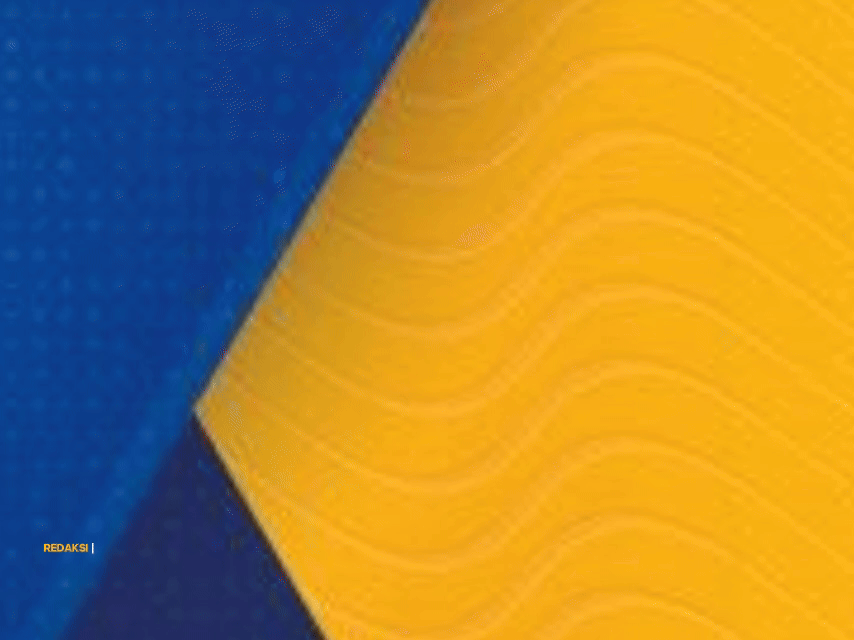Oleh YURNALDI, Pemred Alinianews.com
ALINIANEWS.COM — Gedung DPR RI kerap disebut sebagai “rumah rakyat”. Julukan itu tidak datang begitu saja, melainkan lahir dari semangat demokrasi yang menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. DPR adalah perpanjangan tangan rakyat, ruang aspirasi, sekaligus forum pengambilan keputusan yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik.
Namun kenyataan di lapangan justru memperlihatkan paradoks yang menyakitkan. Ketika rakyat datang berbondong-bondong ke Senayan untuk menyampaikan aspirasi, pintu DPR justru ditutup rapat, dijaga ketat, bahkan dilumuri oli agar tidak bisa ditembus. Ironi ini menohok: rumah rakyat berubah menjadi benteng kekuasaan.
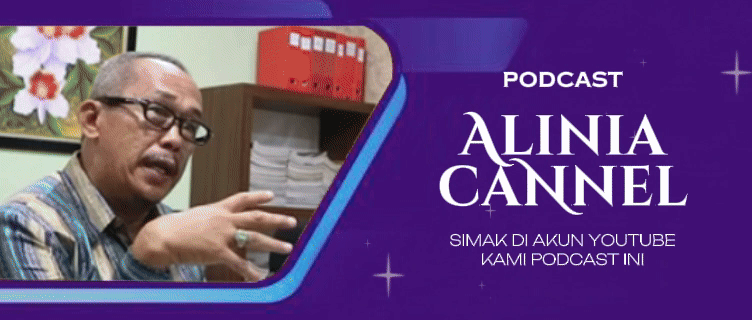
Kontradiksi Ucapan dan Tindakan
Ketua DPR RI pernah menyatakan bahwa pintu parlemen selalu terbuka bagi rakyat yang ingin menyampaikan pendapat. Sebuah pernyataan manis yang terdengar indah di ruang media. Namun peristiwa di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Ketika ribuan bahkan ratusan ribu rakyat benar-benar datang, mereka justru dihadapkan pada pintu yang terkunci.
Tindakan ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah DPR benar-benar terbuka untuk rakyat, atau hanya untuk kepentingan politik dan kekuasaan tertentu? Bukankah wakil rakyat seharusnya berani berdialog dengan rakyat, meski tuntutannya keras, bahkan pahit?
Rakyat Sebagai Ancaman
Oli hitam yang dilumuri di gerbang DPR bukan sekadar cairan, melainkan simbol. Ia adalah simbol kotor dari relasi kuasa yang terbalik. Rakyat, yang seharusnya diposisikan sebagai pemilik kedaulatan, justru dianggap ancaman yang harus ditahan dengan pagar, kawat berduri, dan strategi penghalangan.
Padahal, aspirasi yang dibawa rakyat ke gedung DPR bukanlah peluru tajam. Itu hanyalah suara, tuntutan, dan keresahan yang ingin mereka sampaikan. Jika DPR menolak untuk mendengar, maka wajar bila muncul anggapan bahwa DPR tidak lagi mewakili rakyat, melainkan hanya menjadi benteng pertahanan elit yang takut kehilangan kenyamanan.
Legitimasi yang Runtuh
Setiap anggota dewan duduk di kursi Senayan berkat mandat rakyat. Tanpa mandat itu, mereka hanyalah individu biasa, bukan wakil rakyat. Namun mandat bukanlah cek kosong. Ia bisa hilang bila kepercayaan rakyat dikhianati.
Menutup pintu dari rakyat adalah cara paling cepat untuk meruntuhkan legitimasi. Rakyat akan bertanya: untuk siapa sebenarnya mereka duduk di kursi empuk itu? Untuk rakyat yang mengetuk pintu, atau untuk kepentingan penguasa yang mereka layani?
Ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada DPR, konsekuensinya serius. Demokrasi menjadi rapuh, dan saluran formal aspirasi runtuh. Yang tersisa hanya jalan nonformal: aksi massa yang lebih besar, tekanan publik di jalanan, bahkan potensi instabilitas politik.
Bahaya Menutup Diri
DPR tampaknya lupa bahwa semakin pintu ditutup, semakin besar tekanan di luar. Menolak 200 ribu rakyat yang datang bukan menyelesaikan masalah, tapi menimbun bara. Jika jumlah itu berkembang menjadi sejuta, apakah pintu akan tetap ditutup? Sampai kapan mereka bisa bertahan dengan strategi penguncian?
Dalam demokrasi, ketakutan wakil rakyat terhadap rakyat sendiri adalah bentuk kegagalan paling telak. Ia menunjukkan bahwa wakil rakyat kehilangan keberanian moral. Mereka nyaman berbicara di podium, tapi gentar berhadapan dengan suara rakyat di depan gerbang.
Solusi: Membuka Dialog, Bukan Pagar
Solusi dari masalah ini sebenarnya sederhana, meski membutuhkan keberanian. DPR harus kembali kepada prinsip dasarnya: berdialog dengan rakyat.
1. Menerima perwakilan demonstran. Pimpinan DPR seharusnya berani duduk satu meja dengan perwakilan massa, mendengarkan aspirasi mereka tanpa takut.
2. Transparansi agenda. Aspirasi yang masuk harus ditindaklanjuti secara terbuka, dibahas dalam sidang, dan dipublikasikan agar rakyat tahu bahwa suara mereka diperhatikan.
3. Membangun komunikasi publik. DPR tidak bisa hanya bicara melalui media. Mereka perlu turun langsung, membuka ruang diskusi dengan kelompok sipil, mahasiswa, purnawirawan, dan semua elemen masyarakat.
4. Menghentikan politik pagar. Menambah pagar, kawat berduri, atau melumuri oli di gerbang bukanlah solusi. Itu hanya memperkuat simbol keterasingan DPR dari rakyatnya.
Demokrasi Bukan Benteng Tertutup
Demokrasi hanya hidup jika ada ruang terbuka antara rakyat dan wakilnya. Ketika ruang itu ditutup, maka demokrasi berubah menjadi sekadar formalitas tanpa jiwa. Gedung DPR boleh megah, tapi bila isinya adalah ketakutan, maka ia hanya sekadar benteng kosong.
Sejarah bangsa ini mengajarkan bahwa suara rakyat tidak pernah bisa dibungkam dengan pagar atau aparat. Semakin diabaikan, semakin besar gelombang perlawanan. DPR harus belajar dari sejarah, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Saatnya Membuka Pintu
Jika DPR benar rumah rakyat, maka pintunya tak boleh terkunci dari rakyat. Menutup pintu hanya akan menumbuhkan jarak dan kemarahan. Demokrasi tidak bisa hidup di balik pagar kawat berduri, melainkan di ruang dialog yang jujur dan terbuka.
Oli di gerbang DPR hari ini adalah simbol kotor dari demokrasi yang terciderai. Tetapi sejarah masih memberi kesempatan: apakah DPR mau membersihkan simbol itu dengan keberanian, atau membiarkannya menghitam hingga menenggelamkan legitimasi mereka sendiri?
Pada akhirnya, rakyat akan selalu mengetuk pintu. Pertanyaannya tinggal satu: apakah DPR akan membuka, atau terus bersembunyi di balik benteng kekuasaan yang rapuh?