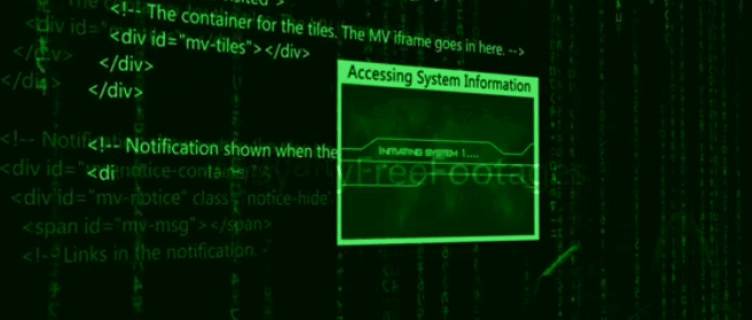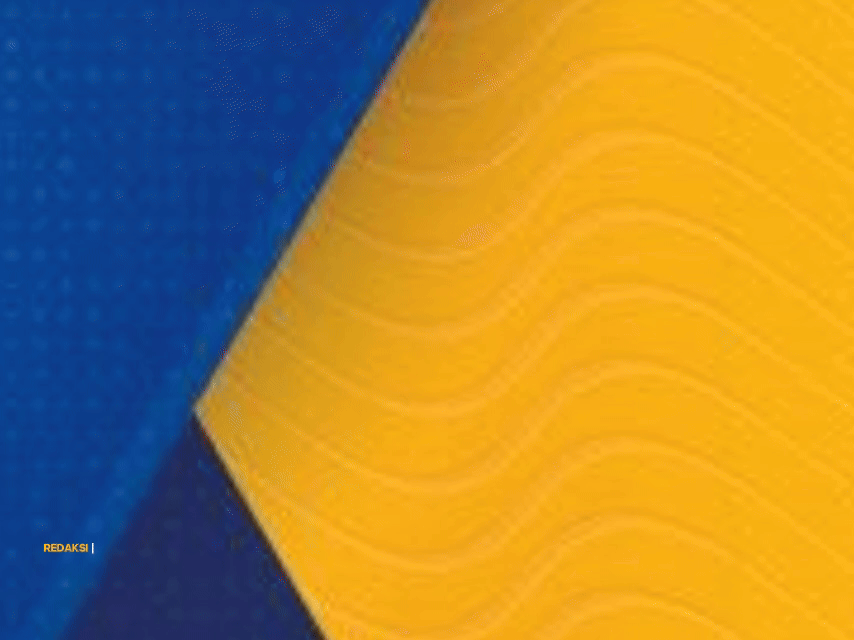ALINIANEWS.COM — Larangan televisi menayangkan demonstrasi adalah sinyal berbahaya. Ia bukan sekadar keputusan teknis penyiaran, melainkan bentuk pembungkaman media. Indonesia seperti sedang “menunggu kemarin”—mengulang pola lama saat informasi hanya boleh keluar dari mulut penguasa.
Publik bereaksi keras. Netizen menyerbu akun KPI, menuding lembaga itu sudah kehilangan marwah. Mereka menolak dibohongi, menolak dibungkam. “Kalau media dibungkam, pakai media kita sendiri!” begitu suara yang menggema di jagat maya.
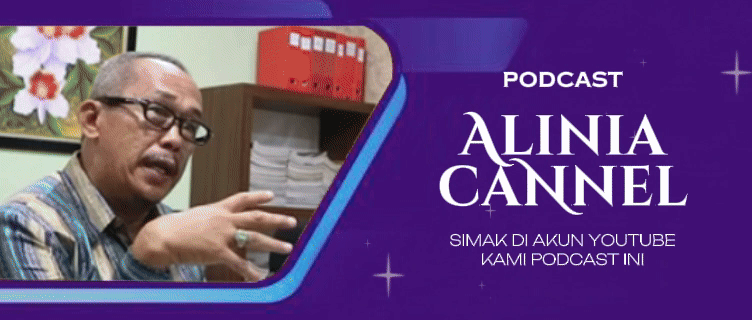
Inilah paradoks zaman. Pemerintah mungkin bisa mengendalikan layar kaca, tapi tak akan pernah mampu mematikan kamera di saku setiap warga. Ponsel, Twitter, Instagram, TikTok—semua menjadi senjata kolektif untuk mendokumentasikan dan menyebarkan kebenaran. Semakin dibatasi, semakin deras arus informasi alternatif.
Dampaknya jelas. Pertama, televisi kehilangan relevansi. Saat rakyat merasa TV hanya corong kekuasaan, kepercayaan runtuh. Kedua, framing negara makin mudah dipatahkan oleh jurnalisme warga. Kekerasan yang ditutup-tutupi justru akan viral tanpa kendali. Ketiga, citra Indonesia di mata dunia makin terpuruk, sebab media asing tetap menyiarkan apa yang justru disembunyikan di dalam negeri.
Sejarah membuktikan, sensor selalu berakhir dengan bumerang. Orde Baru pun runtuh ketika teknologi informasi mulai menembus tembok-tembok sensor. Kini, dengan media sosial yang tak terbendung, upaya menutup mata publik hanyalah ilusi.
Negara seharusnya belajar: jalan terbaik bukan menutup berita, tapi mencegah kekerasan itu sendiri. Kalau tak ingin aksi represif disiarkan, maka jangan ada kekerasan. Sesederhana itu. (YURNALDI)