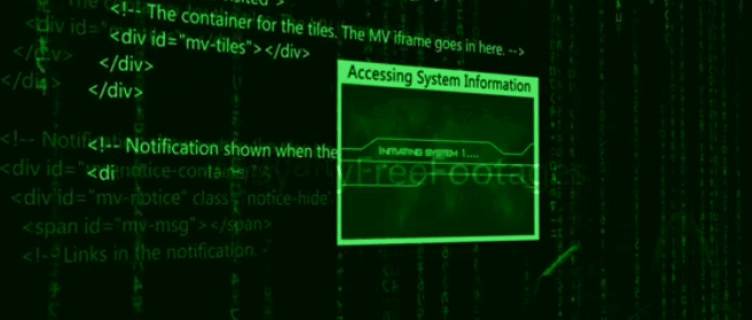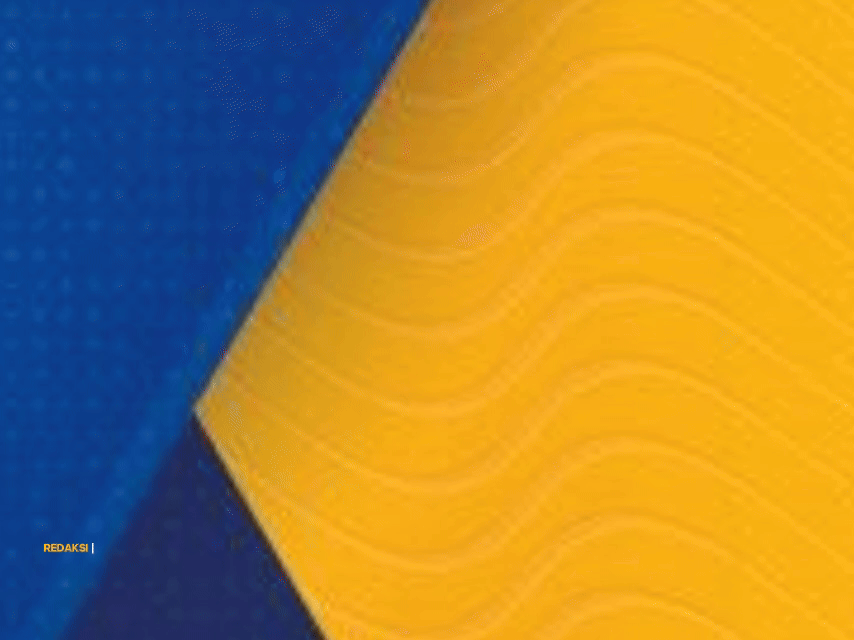Oleh Denni Meilizon
Foto: Eko Darmawan
KINALI, ALINIANEWS.COM — Sore itu, jalan di hadapan kami seperti ular panjang yang berliku dan berbatu. Mobil jemputan yang diutus perusahaan berguncang keras setiap kali roda menghantam kerikil tajam, sementara debu menempel di kaca seolah menolak untuk dihapus.
Kami, rombongan kecil dari Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat, memulai perjalanan menuju pemukiman karyawan PT Primatama Mulia Jaya (PMJ) di Kinali. Kata orang, jaraknya tak lebih dari satu setengah jam dari Simpang Ampek, tapi rasanya lebih jauh karena sepanjang perjalanan hanya ada hutan sawit yang seakan tak berujung.
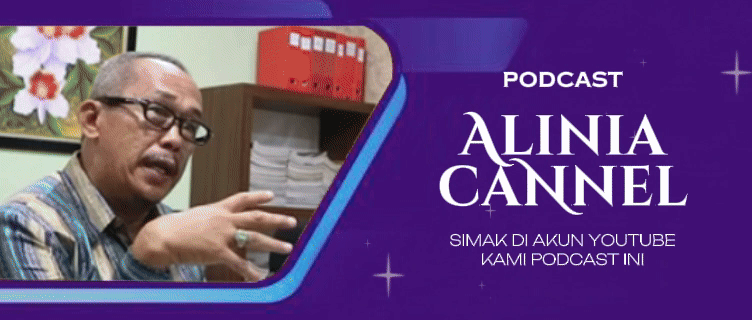
Di kiri dan kanan jalan, batang-batang sawit menjulang seragam, barisan tentara hijau yang menutupi segala kemungkinan lain. Sesekali kami melewati bandar kecil, airnya bening memantulkan cahaya matahari. Rasanya segar sekali hanya dengan melihatnya. Saya sempat berkelakar dalam hati: kalau lain kali diundang lagi, bagus juga membawa kail dan joran. Siapa tahu, sambil menunggu acara, bisa memancing ikan di sungai yang jernih ini. Tapi lelucon itu cepat pupus ketika papan peringatan “AWAS BUAYA” menegakkan bulu kuduk. Ternyata, di balik jernihnya air, ada rahasia yang harus dihormati.

Perjalanan seperti ini mengingatkan saya: jalan menuju literasi pun kerap penuh rintangan. Tidak selalu mulus beraspal, kadang berbatu, berdebu, bahkan berbahaya. Namun di sela-selanya, selalu ada “air jernih” yang membuat kita merasa segar, merasa berharga.
Pemukiman Nias di Tengah Perkebunan
Setelah berguncang cukup lama, akhirnya kami tiba di sebuah pemukiman. Rumah-rumah sederhana berjajar, sebagian dari kayu, sebagian semi permanen. Di halaman, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, wajah mereka penuh rasa ingin tahu melihat mobil kami masuk. Mereka tertawa, sebagian bersembunyi di balik punggung ibunya, lalu muncul lagi dengan mata berbinar.
“Selamat datang!” sambut seorang bapak yang kemudian memperkenalkan diri sebagai perwakilan perusahaan. Kami pun disambut dengan hangat, meski di tengah teriknya matahari perkebunan yang masih menyala di sore itu.
Saya baru tahu, pemukiman ini sebagian besar dihuni oleh saudara-saudara kita dari suku Nias. Orang-orang yang dalam bahasa mereka disebut Ono Niha—anak manusia. Mereka datang jauh dari Pulau Nias, Tanö Niha, menyeberang laut, lalu menanam hidup baru di tanah perkebunan sawit. Di perantauan, identitas mereka tetap kuat: bahasa Nias masih terdengar di antara percakapan ibu-ibu, sementara anak-anak menyelipkan kata Minang dalam logat khas mereka.
Suku Nias sejak lama dikenal sebagai perantau tangguh. Tanah asal mereka di barat Sumatera, meski indah dengan pantai dan tradisi lompat batu yang tersohor, terbatas dalam peluang kerja. Maka, merantau menjadi pilihan: dari Medan, Riau, hingga Pasaman Barat. Dan di sini, di tengah sawit, mereka membangun rumah dan keluarga.

Hari Anak Nasional di Tanah Rantau
Kami datang bukan untuk meneliti atau menggurui, melainkan untuk merayakan Hari Anak Nasional bersama mereka. Perwakilan perusahaan mengundang Forum Pegiat Literasi agar anak-anak dan keluarga mendapat “hadiah” berbeda dari rutinitas sehari-hari.
Lapangan kecil di tengah pemukiman seketika dipenuhi tawa. Ada Tempat Penitipan Anak yang hari ini disulap jadi semacam aula. Anak-anak duduk lesehan, sebagian berdiri sambil bersorak. Kami membuka acara dengan permainan edukatif sederhana: siapa cepat menjawab pertanyaan, siapa berani maju bernyanyi. Pertanyaannya tentang pengetahuan Pancasila. Nyanyinya lagu-lagu nasional. Suasana riuh. Ada yang malu-malu, ada yang percaya diri. Saya melihat betapa antusiasnya mereka, meski aula ini sederhana hanya beralas tikar.
Seorang kawan saya yang akrab kami panggil Ni Wilda bercerita dengan penuh ekspresi, mendongeng tentang persahabatan seekor burung kecil dan pohon yang dermawan. Anak-anak terdiam, lalu tertawa pada bagian lucu, matanya terbelalak saat tokoh cerita diuji. Di sela-sela itu, ibu-ibu mendekat untuk mendengarkan materi singkat tentang parenting anak—betapa pentingnya mendengar, mendukung, dan memberi ruang tumbuh bagi si kecil, meski di tengah keterbatasan. Materi ini dibawakan Kak Asda Tan dan Ni Wilda dengan boneka Bunayya-nya.

Dan ketika kami mengajak mereka bernyanyi, suara kecil itu berpadu menjadi paduan suara yang tak kalah merdu dari orkestra mana pun. Ada kebahagiaan yang sederhana namun tulus. Saya sadar, inilah makna perayaan Hari Anak: memberi ruang bagi anak-anak untuk tertawa, merasa dihargai, merasa berarti.
Ketika akan menutup acara, tiba-tiba ada beberapa anak yang berteriak mengacungkan telunjuk, “Bapak, bapak kita baca puisi!” seru mereka nyaris berbarengan. Aha, kaget saya. Saya lirik Mas Eko Darmawan yang ligat buka google mencari puisi perjuangan, karena kami tidak membawa buku puisi. Dan tujuh orang anak tampil membacakan puisi – puisi itu.
Literasi sebagai Jembatan
Bagi kami, kegiatan seperti ini bukan sekadar acara seremonial. Di tengah perkebunan sawit, akses terhadap pendidikan dan bacaan sangat terbatas. Buku-buku jarang, akses kepada pengetahuan minim. Tetapi anak-anak tetap punya rasa ingin tahu. Mereka haus cerita, haus pengalaman. Dan literasi hadir sebagai jembatan—menghubungkan mereka dengan dunia luas di luar kebun sawit.
Literasi tidak hanya soal membaca atau menulis. Ia juga tentang bermain bersama, bernyanyi bersama, mendengar dongeng, bahkan berbicara dari hati ke hati dengan orangtua. Literasi adalah kemampuan untuk memahami diri dan orang lain, untuk bermimpi sekaligus membangun realitas.
Di tengah pemukiman ini, saya melihat betapa literasi mampu menyalakan cahaya kecil di mata anak-anak. Mungkin hanya sehari, mungkin hanya beberapa jam, tapi cahaya itu bisa tumbuh menjadi api jika dipupuk.
Dan bagi orang dewasa—para ayah dan ibu yang sehari-hari bekerja keras di kebun sawit—literasi memberi ruang refleksi: bahwa anak-anak mereka butuh didengar, butuh dipeluk, butuh didampingi dalam tumbuh kembangnya.

Jalan Pulang dan Harapan
Magrib menjelang ketika kami berpamitan. Anak-anak melambaikan tangan, beberapa masih menyanyikan potongan lagu yang tadi kami ajarkan. Saya menoleh sekali lagi ke arah pemukiman, merasa seolah meninggalkan sesuatu yang belum selesai.
Perjalanan pulang kembali melewati jalan panjang yang sama: batu, kerikil, debu, dan sawit yang seragam. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Bandar kecil dengan air jernih yang tadi sempat saya lihat, kini seperti metafora. Di tengah sawit yang monoton, ada aliran jernih yang menyejukkan. Begitu pula, di tengah rutinitas kerja perkebunan yang keras, ada anak-anak Nias dengan mimpi dan tawa mereka.
Saya kembali teringat soal kail dan joran. Mungkin memang bagus jika lain kali dibawa. Tapi lebih dari itu, saya sadar: literasi adalah kail sejati. Dengan itu, kita bisa memancing harapan, membangun jembatan, dan memberi ruang bagi masa depan yang lebih baik.
Dan anak-anak Nias di Kinali, di tengah kebun sawit yang luas ini, adalah alasan mengapa kita harus terus melakukannya.