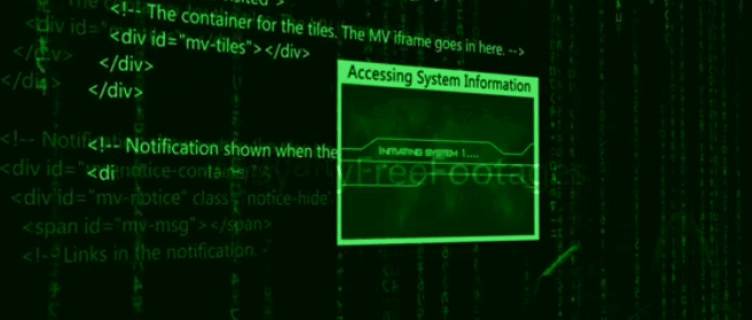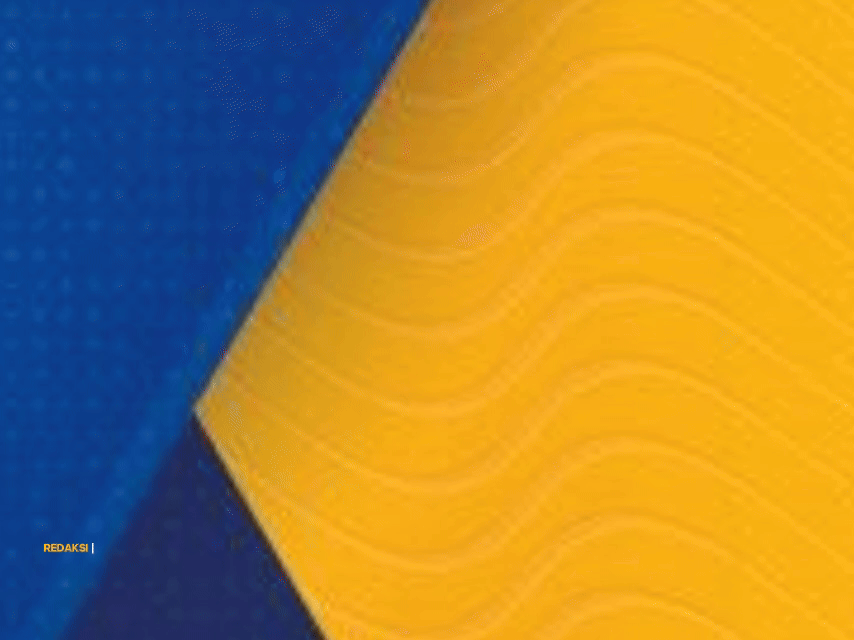Oleh : Drs.H.Marlis,MM, C.Med ( Mantan GURU STM N 1 Lubuk Pakam )
Di tengah upaya bangsa memperbaiki kualitas pendidikan, ada satu kekacauan yang tak kunjung dibereskan: obsesi pejabat terhadap istilah, singkatan, nomenklatur, dan perubahan nama. Fenomena ini sudah berlangsung bertahun-tahun, namun tetap dibiarkan seolah tidak memiliki dampak apa pun terhadap publik. Padahal, masyarakat — dari orang tua hingga guru — menjadi korban kebijakan yang berubah tanpa henti itu.
Mulai dari nama kementerian yang selalu berganti: Depdiknas, Kemendiknas, Kemendikbud, Kemendikbudristek. Setiap kali nama berubah, standarnya sama: papan nama baru, seragam baru, dokumen baru, anggaran baru. Tidak pernah ada evaluasi: adakah manfaat substantif dari perubahan itu?
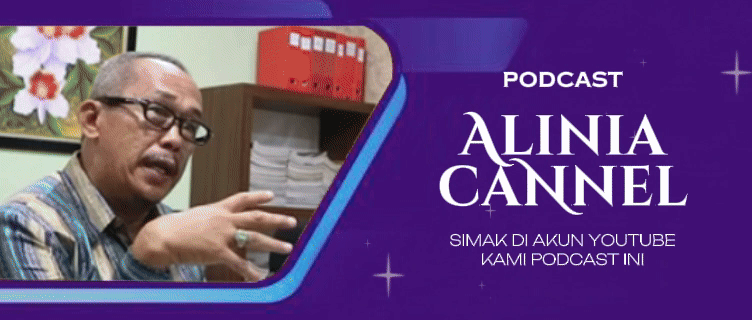
Yang ada justru pemborosan anggaran yang dibungkus jargon modernisasi.
Belum selesai masyarakat memahami nama kementerian, mereka sudah disuguhi drama gonta-ganti kurikulum: KBK—KTSP—K13—Kurikulum Merdeka—Merdeka Belajar Episode sekian.
Setiap menteri punya “warisan” masing-masing, dan kurikulum pun dijadikan panggung ego. Namun di lapangan, guru kelelahan, siswa kebingungan, orang tua kehilangan arah. Ketika publik meminta stabilitas, pejabat justru sibuk melahirkan istilah baru.
Kekacauan serupa juga terlihat pada proses penerimaan siswa dan mahasiswa. PPDB, zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, SNMPTN, SBMPTN, UTBK, SNBP, SNBT—semua berubah cepat seperti upgrade aplikasi. Masyarakat dipaksa terus mengikuti perubahan yang tidak pernah disosialisasikan dengan layak.
Belum lagi urusan nama jenjang pendidikan: SMP berubah menjadi SLTP, lalu kembali lagi ke SMP. SMU menjadi SMA, lalu dipertanyakan lagi.
Setiap pergantian nomenklatur berarti biaya: cat ulang papan sekolah, dokumen administrasi, blanko ijazah, seragam, hingga perangkat digital.
Pertanyaannya: siapa yang paling diuntungkan dari perubahan istilah ini?
Masyarakat melihat fenomena ini dengan sinis. Sebab terlalu banyak jejak yang mengarah pada pemborosan anggaran dan peluang korupsi. Setiap perubahan selalu ada proyeknya.
Sementara publik hanya bisa mengeluh pelan, pejabat dengan bangga berdiri di atas podium—meluncurkan istilah baru yang terdengar keren tetapi tak menyelesaikan masalah.
Kini masyarakat sudah muak.
Muak dengan kebijakan yang lebih memprioritaskan “branding” daripada substansi.
Muak dengan istilah yang terus berganti tanpa peningkatan kualitas layanan.
Muak dengan birokrasi pendidikan yang semakin rumit, bukan semakin memudahkan.
Karena itu, lewat tulisan ini, masyarakat menyampaikan seruan tegas:
Wahai Menteri, para Dirjen, dan jajaran pejabat pendidikan—cukup sudah.
Hentikan parade istilah. Hentikan jualan ego. Hentikan pemborosan anggaran negara.
Bangunlah sistem pendidikan yang konsisten, efisien, dan berpihak kepada rakyat.
Indonesia tidak butuh singkatan baru. Indonesia butuh kebijakan yang benar-benar bekerja. (*/Marlis Alinia )