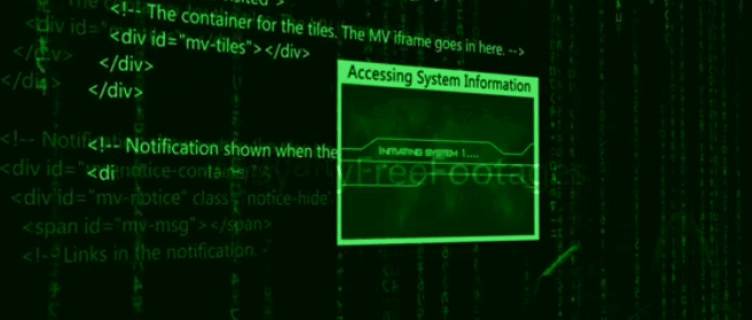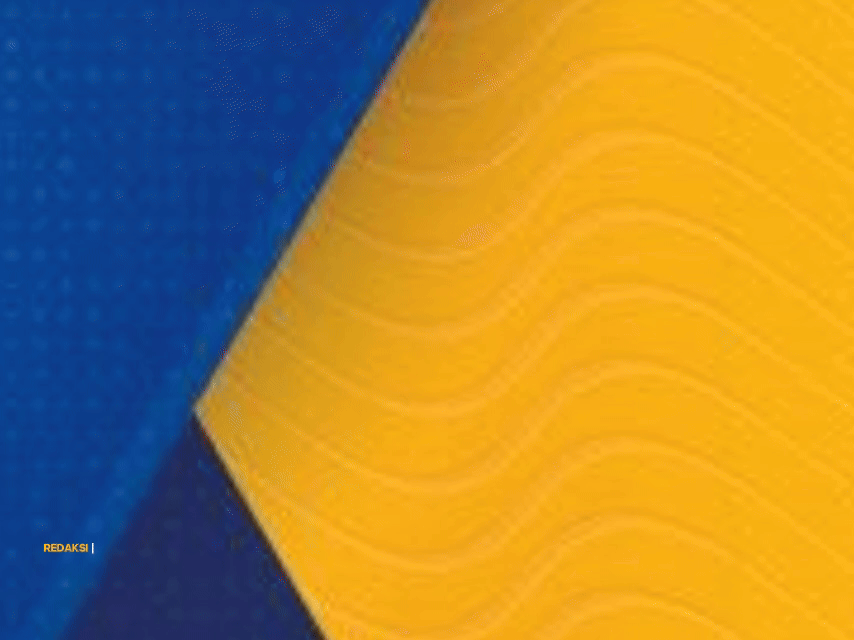ALINIANEWS.COM — Di negeri ini, menjadi warga yang taat pajak ternyata bukan hanya tidak dihargai, tapi malah dipersulit.
Satu contoh nyata: seorang suami hendak membayar pajak kendaraan atas nama istrinya yang sedang berada di luar kota. Ia datang ke kantor Samsat, mengantre dengan tertib, membawa dokumen lengkap, dan berniat melunasi kewajiban sebelum jatuh tempo. Tapi apa yang ia dapat? Penolakan. Sistem pelayanan menolaknya karena nama di STNK tak sama dengan identitas pembayar, meski keduanya adalah suami-istri dan kendaraan milik rumah tangga mereka. Layanan keras kepala, birokrasi kaku, dan akal sehat dikesampingkan.
Ironisnya, pada saat yang sama, pemerintah daerah justru sibuk mengiklankan “pemutihan pajak” besar-besaran: membebaskan denda, memberi diskon, bahkan menghapus kewajiban masa lalu bagi para penunggak. Singkatnya: kalau kamu melanggar, kamu diberi hadiah. Kalau kamu patuh, kamu dipersulit.
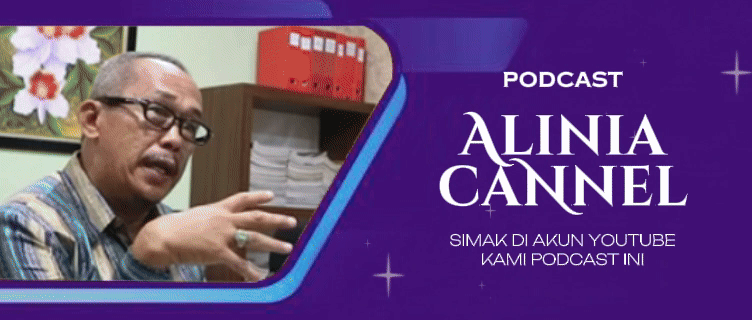
Di mana keadilan sosialnya?
Pola seperti ini bukan hanya menyinggung rasa keadilan publik, tapi juga membentuk mental kolektif baru: menunggak dulu, nanti juga dimaafkan. Pemerintah secara tak sadar tengah merawat budaya malas bayar pajak dengan kebijakan populis jangka pendek. Demi mengejar angka penerimaan, negara membiarkan prinsip moral kepatuhan hancur di tangan promosi pemutihan.
Tak heran, warga yang kecewa lalu berpikir: “Kalau begitu, buat apa saya bayar sekarang? Lebih baik tunggu lima tahun, nanti juga dapat pemutihan.” Maka satu orang taat yang dikecewakan bisa berubah menjadi lima tahun kehilangan pendapatan pajak. Multiply itu secara nasional, dan Anda akan melihat kebangkrutan moral fiskal.
Masalah ini bukan semata tentang siapa yang membayar. Ini soal bagaimana negara memperlakukan warganya. Bila warga dengan niat baik pun tidak diberi ruang untuk memenuhi kewajiban, lalu apa fungsi negara dan sistem pelayanannya? Bukankah seharusnya sistem digitalisasi dan reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan bisa menjawab hal-hal semacam ini?
Namun faktanya, negara lebih senang menjadikan rakyat sebagai sasaran pelatihan disiplin, ketimbang sebagai mitra yang dipercaya. Hukum administrasi tak memberi ruang untuk akal sehat, apalagi empati.
Sudah cukup kegagalan kita dalam membangun kepercayaan publik. Jika pemerintah masih ingin warga patuh membayar pajak, maka perlakukan yang patuh sebagai aset, bukan sebagai pengganggu sistem. Jangan biarkan yang jujur merasa bodoh, dan yang melanggar malah merasa beruntung.
Jika pemerintah sungguh ingin meningkatkan kepatuhan pajak, maka yang pertama harus dibenahi adalah logika pelayanan. Orang yang taat harusnya dipermudah, bukan dipersulit. Pemberian insentif harus adil, bukan memberi karpet merah kepada penunggak, sambil memukul mundur yang taat.
Sudah saatnya kita mengevaluasi ulang paradigma pelayanan pajak kendaraan bermotor: apakah ia masih berpihak kepada warga negara yang bertanggung jawab, atau justru melanggengkan ketidakadilan yang terstruktur dalam birokrasi.
Pemerintah daerah harus ingat: taat pajak adalah hasil dari kepercayaan, bukan karena ketakutan. Dan kepercayaan itu rapuh — ia tumbuh dari rasa adil, dan tumbang oleh birokrasi bebal. (YURNALDI)